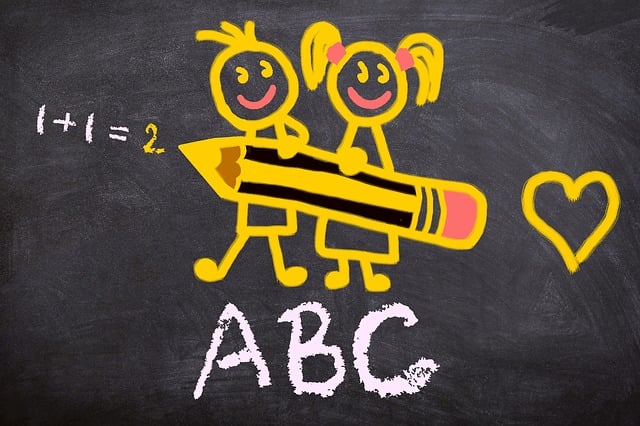Dalam sistem pendidikan kita hari ini, angka telah menjadi penentu segalanya. Yang dikejar bukan lagi pemahaman, tapi rapor yang baik. Yang dikhawatirkan bukan ketidaktahuan anak, tapi kesan buruk di mata publik. Maka muncullah kultur pendidikan yang tak sehat: anak harus dapat nilai bagus, walau ia belum tentu paham.
Tekanan itu datang dari segala penjuru:
• Sekolah dikejar target kelulusan 100% demi akreditasi dan citra lembaga. Akreditasi A menjadi obsesi, bukan sebagai tolok ukur mutu riil, tapi sebagai “surat sakti” menarik siswa dan anggaran.
• Orang tua merasa gagal secara sosial jika anaknya tidak mendapat nilai tinggi. Keberhasilan anak dinilai dari ranking dan nilai UN, bukan dari tumbuhnya karakter, semangat belajar, atau kebahagiaan.
• Dinas pendidikan mencurigai sekolah dan guru yang mempertahankan siswa agar tidak naik kelas. Alih-alih memberi dukungan pedagogis, sistem justru menekan agar tidak ada “catatan negatif”.
📊 Menurut data Kemendikbudristek tahun 2022, 98,7% siswa SD dan SMP dinyatakan lulus. Angka ini terlihat membanggakan. Tapi jika disandingkan dengan data PISA 2022, di mana Indonesia mencatat skor rendah pada literasi membaca, matematika, dan sains, terlihat ada yang tidak selaras: siswa “lulus” hampir semua, tapi pemahaman akademik mereka minim.
Ada keganjilan struktural di sini: ketika hampir semua murid lulus, tapi kemampuan dasar mereka jauh di bawah rata-rata global. Maka lulus bukan lagi tanda keberhasilan belajar, tapi indikator ilusi sistemik.
Manipulasi Nilai dan Ilusi Kemajuan: Ketika Kebenaran Dikorbankan demi Angka
Dalam praktiknya, manipulasi nilai terjadi bukan karena guru ingin curang, tapi karena sistem membuat mereka tidak punya pilihan lain.
📌 Laporan Komisi X DPR RI tahun 2023 menunjukkan adanya tren “penyesuaian nilai massal” yang terjadi menjelang pengisian rapor digital. Guru-guru merasa terpaksa menaikkan nilai untuk menghindari evaluasi negatif dari dinas atau kepala sekolah. Bahkan beberapa daerah memiliki “batas bawah” nilai yang tak boleh dilanggar, seolah kesalahan belajar siswa harus ditutupi demi reputasi sekolah.
Fenomena ini bisa disebut sebagai fraud edukatif sistemik—pemalsuan yang tidak lagi bersifat individual, tapi melembaga dan masif. Dan bahayanya, sistem ini melahirkan generasi yang:
• Terbiasa mendapat hasil tanpa usaha.
• Takut pada kejujuran karena sistem tidak melindungi yang jujur.
• Percaya bahwa penampilan lebih penting dari proses.
Ini bukan sekadar soal etika pendidikan. Ini soal masa depan bangsa. Sebab bangsa yang besar tidak mungkin dibangun oleh generasi yang dilatih dalam kepalsuan.
Dampak Psikososial, Generasi yang Rapuh tapi Merasa Hebat
Kultur “nilai harus bagus” menciptakan tekanan psikologis yang sangat berat pada anak. Anak-anak yang seharusnya sedang bertumbuh justru dicekoki narasi bahwa nilai adalah segalanya. Mereka tidak diberi ruang untuk gagal, mengevaluasi diri, dan tumbuh dari kesalahan.
📉 Hasil survei KPAI tahun 2022 mencatat bahwa 23% anak usia sekolah mengalami gangguan psikis akibat tekanan akademik, seperti kecemasan berlebih, depresi ringan, hingga kelelahan mental. Semua itu terjadi karena nilai menjadi alat ukur tunggal, bukan pembelajaran holistik yang mencakup karakter, keberanian, kerja sama, dan kepedulian.
Lebih dari itu, anak-anak terbiasa meraih hasil yang tidak merepresentasikan kerja kerasnya. Ini membentuk apa yang disebut oleh pakar pendidikan Alfie Kohn sebagai “false achievement orientation”—yaitu kebiasaan merayakan keberhasilan palsu, yang dalam jangka panjang justru menggerus rasa tanggung jawab dan resiliensi anak.
Akar Masalah, Budaya Ukur Cepat dan Citra Instan
Jika ditelusuri lebih dalam, problem ini bukan hanya soal kebijakan teknis, tapi budaya sosial: budaya “serba cepat”, “serba instan”, dan “serba tampak bagus.”
Masyarakat kita lebih menghargai citra ketimbang proses. Laporan pendidikan seringkali penuh grafik yang naik, bukan analisis mendalam soal proses dan tantangan pembelajaran.
Kita lebih suka anak “naik kelas” daripada jujur bahwa ia butuh waktu untuk paham. Kita lebih suka melihat rapor penuh angka 80-an, daripada mendengar guru berkata bahwa anak sedang belajar dengan proses bertahap.
Sistem ini akhirnya membentuk lingkaran setan:
Sekolah ditekan orang tua → guru terpaksa memoles nilai → murid kehilangan semangat belajar → hasil belajar rendah → sistem tidak berubah → kembali ke awal.
Rekonstruksi: Dari Budaya Angka ke Budaya Belajar
Untuk membongkar kultur ini, diperlukan keberanian bersama:
1. Mengubah indikator evaluasi pendidikan dari sekadar angka ke asesmen berbasis proses, minat, dan karakter.
2. Melindungi guru jujur, bukan mencurigainya. Guru yang menilai dengan objektif harus didukung, bukan ditekan.
3. Melatih orang tua untuk memahami dunia anak, bukan sekadar memproyeksikan impian masa lalunya ke dalam rapor anak.
4. Memulihkan makna belajar sebagai proses manusiawi—dengan ruang untuk gagal, mencoba lagi, dan bangga atas usahanya sendiri.
🔖 Jika yang kita kejar hanya nilai, maka yang kita bentuk adalah generasi angka. Tapi jika yang kita bangun adalah semangat belajar, maka kita sedang menciptakan peradaban.
Dan peradaban sejati tidak dibangun oleh angka yang dibagus-baguskan. Ia dibangun oleh anak-anak yang belajar dengan jujur, guru yang mengajar dengan nurani, dan masyarakat yang memahami bahwa kebenaran jauh lebih penting daripada tampilan. Siapkah kita mengembalikan pendidikan ke jalan yang seharusnya? (Bersambung ke bagian 3).
Kembali ke bagian pertama: Murid Tak Boleh Gagal, Pendidikan dalam Kepalsuan
Oleh Mangesti Waluyo Sedjati
Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah
Sumber: mangestiwrites.wordpress.com
Foto: pixabay